Cerpen 'Mengasuh Maut'
Ada
tujuh rumah, berisolasi yang diisi teriakan-teriakan. Liris-liris garis
besi, dibalut cat minyak hitam. Rumah-rumah yang dihuni dari ratusan
ribu kilometer. Di ujung kali, sebatas pandangan mata orang-orang biasa
pun tak kan mampu menemukannya. Kapal-kapal pernah berlalu lalang,
corong asapnya sangat jauh, begitu jauh. Sebab itulah jika malam hari
hanya ada deburan ombak yang menampik batang hutan bakau. Orang-orang di
zaman orde sebelumnya sibuk menanami daerah ini dengan bakau. Agar esok
bisa menjadi sebuah pulau dengan daya tarik wisata yang besar, dan
pasti akan dikagumi oleh masyarakat dunia. Tak ada kesibukan, hanya ada
beberapa pria-pria berkumis tebal, lengkap dengan busana hitam yang
menambah tubuhnya semakin gempal.
Dalam hisapan rokoknya, pertama, kedua dan yang ketiga ia melirik dibalik baju-baju. Berjalan di koridor gelap, dengan genggaman senter di tangan kiri. Orang-orang terdiam, seketika pula Marham duduk menunggu ia lewat tepat di depan selnya. Dalam kurungan itu, Marham hanya bisa duduk dan terkungkung persis seperti janin bayi. Ia melekuk kedinginan, sebab hujan deras tak berhenti semenjak sore. Marham duduk mengeja, menulis tirus hitungan-hitungan hari sebelum ia menuju hari penghakiman.
Orang-orang di kampungnya sudah membela sekuat tenaga. Marham adalah salah satu korban menurut mereka. Ada petani yang datang membela dengan cangkulnya. Cangkul itu ia bawa-bawa ke sidang pengadilan, begitu juga dengan seorang peladang, ia dengan tangkas mengaitkan sangkurnya di pinggang, adapun seorang guru duduk menuliskan apa-apa saja kesalahan yang dilakukan Marham, dan apa kesalahan yang dilakukan oleh hakim untuk bisa naik banding jika ke depan Marham tetap dihukum.
Marham semakin kurus. Bibirnya kelam dipulas abu, kepalanya plontos dan lapang persis seperti lapangan bola. Bibirnya sesekali bergetar, mungkin sudah lama ia tak melihat wajah orang-orang, serta kilatan kamera yang sengaja dipetik orang-orang yang haus akan pemberitaan tentangnya. Dalam kedalaman sunyi, terbetik sebuah kisah pilu tentang berita yang akan dilongok oleh seisi dunia. Kisah hancurnya peradaban manusia, dari sebuah sperma hingga mencium tanah di lapangan tembak.
Maut Marham, akan menjadi pemberitaan orang-orang dan menjadi berita di teras utama. Marham makin bergetar, wajahnya pucat. Orang-orang memanggil namanya.
“Marham... Marham..., kau tidak bersalah”
“Pak Marham bagaimana dengan penebusan? Atau jaminan apakah pengadilan menerimanya? Bapak tidak mengajukan banding?”
Marham tak bergeming, ia berlalu dengan sedikit mengepulkan asap-asap tembakau, orang-orang larut dalam asapnya, tak punya beban, hanya kabut tipis yang dimulai oleh hisapan mulut manusia. Marham duduk, pegangan kursi diketuk-ketuk bergantian dengan lima jarinya. Ia menatap majelis hakim dan orang-orang bersiap menunggu apa hasil putusan. Banyak yang bergembira namun lebih banyak yang akan membenci pikir Marham. Dibalik busana putih tipis, ia persis seperti orang-orang yang digambarkan dari langit. Ia datang dari penduduk langit dan bersiap kembali ke langit.
Ada beberapa teman sebayanya yang mengeluarkan biji matanya, mereka bersiap menggebrak meja hakim, tapi putusan telah diambil. Palu telah diketuk. Marham digiring kembali menuju sebuah lorong menuju surga. Ya, disinilah orang-orang akan pergi menuju dunia berikutnya. Entah, ia akan masuk ke kanan surga atau kekiri lewat neraka. Dalam cerita-cerita yang bertebaran di masyarakat di daratan seberang pulau itu, akan ada banyak tulang-tulang yang berserakan di tubuh pantai, di balik bakau yang meracau setelah dihepas ombak.
Ia menaiki sebuah kapal besar yang diisi oleh tahanan-tahanan serupa untuk melewati satu pulau lagi, lalu pergi dan siap berpancang di terik matahari lalu ditembus oleh bijih besi dan lenyap dalam berita di koran-koran. Ia sudah melanglangkan pikirannya jauh masuk ke dalam suasana itu. Sementara tubuhnya telah sampai di tengah laut, ternyata Marham kembali harus berpindah perahu untuk menerima maut.
Begitu aibnya diri Marham, mungkin itu yang terkesiap di kepala algojo-algojo untuk menjauhkan Marham dari daratan yang dipijak oleh orang banyak. Sementara Marham, punya satu keinginan yang besar, bahwa ia ingin mati di kampung sendiri. Marham kini sudah dibawa jauh ribuan kilometer dari masa kecilnya, masa dimana ia mengenang suara-suara teriakan dari ibunya, memanggil ketika ia lupa waktu meloncat ke sungai, mencari ikan dan bertabuh gendang dalam air. Suara Marham yang paling nyaring, apalagi kalau mereka sudah bergelut dalam keruhnya sungai di dekat rumah. Ibunya paling kesal jika melihat Marham, lupa waktu. Ibunya tak ingin Marham melupakan shalat, sebab dalam shalat ada takwa yang sudah dijanjikan Tuhan.
“Marham, pulang!!!”
Kalau saja Marham sudah mendengar hal itu, ia lantas bergerak cepat. Menyusup di antara semak dan jalan setapak, ia lebih rela menyayat lengannya dengan tajamnya duri daripada harus bertemu dengan ibunya yang sudah menunggu di simpang jalan setapak bersama sebatang kayu bakar. Marham langsung meninggalkan sahabatnya. Ia berpacu dengan waktu untuk sampai ke rumahnya terlebih dahulu, membersihkan diri dan duduk untuk berpura-pura seakan-akan ibunya salah perkiraan. Ia duduk rapi di atas dipan reot yang dahulu dipahat bapaknya.
Marham tersenyum ketika ibunya datang. Apa yang bisa dilakukan seorang Ibu, ketika ia tak menemukan anaknya dalam keadaan bersih dan sedang menunggu datangnya Azan Maghrib. Ibunya hanya bisa tersenyum, meskipun ini sudah dilakukan Marham beratus kali, hampir setiap. Marham pun tersenyum dan mencium tangan ibunya.
“Marham kau memang pelita di hati Ibuk. Semenjak kepergian Bapakmu, kau lah yang menjadi penghibur hati dan kesepian di rumah ini”
Ya, kampung itulah, tepat dibelakang rumahnya ada kuburan Bapaknya. Disana ia ingin dikuburkan, dalam ketenangan desa dan sungai-sungai yang melaraskan alirannya lembut melewati bebatuan. Di kampung sunyi, sepi dan dipenuhi dengan teriakan bocah-bocah dari kejauhan tentang sungai-sungai, serta kebahagiaan.
Sebelum akhirnya ketika dewasa Marham beranjak dewasa dan mengenal kota. Ia liar seperti singa yang mengaum di tengah jalanan. Ia dibesarkan dari lorong ke lorong. Ia tinggalkan Ibunya, lantas mencari Ibukota. Ia menukar harapan kosong di kampung dengan gemerlapan wajah dunia. Setiap malam, ia duduk di gang-gang dengan sebilah belati tersarung di pinggangnya. Kalau sepi, ia beralih ke terminal bus antar kota, untuk menampar mimpi orang-orang kampung yang datang dengan harapan. Ia semakin ganas, ia merampas, menjambret dan membuat dirinya semakin kelam.
Dalam beberapa tahun ia menjadi tersohor, siapa yang tak kenal dengan Marham. Ia tak lagi membegal orang-orang, kini ia lebih terhormat. Ia duduk bersama orang-orang berdasi yang tenang menukar uang dengan sekumpulan bubuk terlarang. Marham menjadi mafia kelas kakap. Ia tak lagi turun dari angkutan umum, dari gang menuju gang, kini semua sudah berevolusi. Ia turun dari mobil mewah ke mobil mewah lainnya, ia tak kenal dengan sungai, yang ia sapa hanya suara gemerlapan malam dan suara dentuman musik yang membahana.
Marham tahu, jika saja ia dapat meloloskan transaksinya kali ini, ia akan berhasil menjadi manusia kaya. Dengan limpahan harta, ia besi membeli apa yang ia mau. Marham semakin menggebu, untuk memasukkan narkoba itu ke negara tetangga. Dalam pikirannya, ada hal yang menggerutu, ada bisikan datang dari Ibunya.
“Pelita hati... pelita hati...”
Marham mendengar bisikan gaib itu, menerka bahwa itu adalah panggilan rindu Ibunya. Namun rindu itu bias ke angkasa. Ia kembali meraih stirnya, mengemudikan laju kendaraannya di batas tol kota. Ia bersiap masuk dengan segala trik. Ia sudah menelan beberapa, memasukkan dalam bagasi serta menyusun rapi di pakaiannya. Ia pasti bisa melewati petugas bandara. Ia yakin sekali dengan kemampuannya itu.
Persis seperti penumpang lain, Marham bersiul dan masuk ke bandara. Seakan tak membawa apa-apa ia melenggang kangkung, dan benar saja ia lewat dari pintu pemeriksaan. Ia berhasil, dalam hatinya ada letusan gunung merapi yang membara bahagia. Segera ia melangkah cepat, menaiki eskalator. Pandangannya jatuh ke lantai mengeja langkah cepat, hingga pandangan itu terhenti pada barisan kaki-kaki kekar. Ia melongok pelan ke atas, dan hampir puluhan aparat bersenjata sudah mengepungnya. Marham kaku, terperangkap seperti singa diburu.
Di perahu, algojo itu semakin cepat mengayuh dayungnya. Marham, menghitung berapa lama lagi detik waktunya menemu maut. Matanya ditutup, tangannya diborgol besi, di balik malam yang dingin, kepalanya menciut pucat, gelap. Ada lima algojo yang mendayung, ia merasakan hangat tubuhnya. Tak ada perbincangan disana, lalu memori melintas tentang kampung, kesunyian dan gurau tawa. Bulan yang terang pun, hanya seberkas seperti kilatan cahaya yang menggumam dari kunang-kunang. Marham merasakan, mulai tak ada lagi suara orang-orang di kejauhan, mesin kapal atau apapun itu. Hanya gemericik air, yang didayung dan itu pun semakin pelan. Jantung Marham mendegup kencang, ia dipapah, diturunkan dari perahu.
“Sebentar-sebentar. Maaf, bolehkah penutup mataku dibuka?”
“Tidak bisa!”
“Bahkan untuk manusia yang terakhir kali melihat bulan pun kalian tidak perbolehkan?”, ucap Marham.
Algojo itu membuka penutup matanya, Marham dibawa ke dalam hutan. Disana ada lapangan luas yang terhampar. Marham melihat sekelilingnya dengan terang. Dinding-dinding bisu, lalu pagar berduri, ada anjungan mercusuar yang dijaga dengan senapan laras panjang. Ia terus berjalan dan bergerak menuju tengah lapangan. Disana sudah tegak tiang pancang. Tepat di depan tiang pancang itulah Marham akan mengasuh mautnya. Kembali dirapalkannya wajah kampung dan Ibuknya. Ia berjalan tergopoh ke tengah.
“Maaf, boleh aku berbisik sesuatu?”
Algojo itu pun kembali menuju ke arahnya.
“kuburkan aku di kampungku”
Mereka kembali melangkah menuju gerbang lapangan.
“dorr..., dorr..., dorr..., dorr..., dorr...”***
Rian Kurniawan Harahap
mahasiswa Pascasarjana UNRI. Menulis cerpen di beberapa harian lokal dan nasional.
Dalam hisapan rokoknya, pertama, kedua dan yang ketiga ia melirik dibalik baju-baju. Berjalan di koridor gelap, dengan genggaman senter di tangan kiri. Orang-orang terdiam, seketika pula Marham duduk menunggu ia lewat tepat di depan selnya. Dalam kurungan itu, Marham hanya bisa duduk dan terkungkung persis seperti janin bayi. Ia melekuk kedinginan, sebab hujan deras tak berhenti semenjak sore. Marham duduk mengeja, menulis tirus hitungan-hitungan hari sebelum ia menuju hari penghakiman.
Orang-orang di kampungnya sudah membela sekuat tenaga. Marham adalah salah satu korban menurut mereka. Ada petani yang datang membela dengan cangkulnya. Cangkul itu ia bawa-bawa ke sidang pengadilan, begitu juga dengan seorang peladang, ia dengan tangkas mengaitkan sangkurnya di pinggang, adapun seorang guru duduk menuliskan apa-apa saja kesalahan yang dilakukan Marham, dan apa kesalahan yang dilakukan oleh hakim untuk bisa naik banding jika ke depan Marham tetap dihukum.
Marham semakin kurus. Bibirnya kelam dipulas abu, kepalanya plontos dan lapang persis seperti lapangan bola. Bibirnya sesekali bergetar, mungkin sudah lama ia tak melihat wajah orang-orang, serta kilatan kamera yang sengaja dipetik orang-orang yang haus akan pemberitaan tentangnya. Dalam kedalaman sunyi, terbetik sebuah kisah pilu tentang berita yang akan dilongok oleh seisi dunia. Kisah hancurnya peradaban manusia, dari sebuah sperma hingga mencium tanah di lapangan tembak.
Maut Marham, akan menjadi pemberitaan orang-orang dan menjadi berita di teras utama. Marham makin bergetar, wajahnya pucat. Orang-orang memanggil namanya.
“Marham... Marham..., kau tidak bersalah”
“Pak Marham bagaimana dengan penebusan? Atau jaminan apakah pengadilan menerimanya? Bapak tidak mengajukan banding?”
Marham tak bergeming, ia berlalu dengan sedikit mengepulkan asap-asap tembakau, orang-orang larut dalam asapnya, tak punya beban, hanya kabut tipis yang dimulai oleh hisapan mulut manusia. Marham duduk, pegangan kursi diketuk-ketuk bergantian dengan lima jarinya. Ia menatap majelis hakim dan orang-orang bersiap menunggu apa hasil putusan. Banyak yang bergembira namun lebih banyak yang akan membenci pikir Marham. Dibalik busana putih tipis, ia persis seperti orang-orang yang digambarkan dari langit. Ia datang dari penduduk langit dan bersiap kembali ke langit.
Ada beberapa teman sebayanya yang mengeluarkan biji matanya, mereka bersiap menggebrak meja hakim, tapi putusan telah diambil. Palu telah diketuk. Marham digiring kembali menuju sebuah lorong menuju surga. Ya, disinilah orang-orang akan pergi menuju dunia berikutnya. Entah, ia akan masuk ke kanan surga atau kekiri lewat neraka. Dalam cerita-cerita yang bertebaran di masyarakat di daratan seberang pulau itu, akan ada banyak tulang-tulang yang berserakan di tubuh pantai, di balik bakau yang meracau setelah dihepas ombak.
Ia menaiki sebuah kapal besar yang diisi oleh tahanan-tahanan serupa untuk melewati satu pulau lagi, lalu pergi dan siap berpancang di terik matahari lalu ditembus oleh bijih besi dan lenyap dalam berita di koran-koran. Ia sudah melanglangkan pikirannya jauh masuk ke dalam suasana itu. Sementara tubuhnya telah sampai di tengah laut, ternyata Marham kembali harus berpindah perahu untuk menerima maut.
Begitu aibnya diri Marham, mungkin itu yang terkesiap di kepala algojo-algojo untuk menjauhkan Marham dari daratan yang dipijak oleh orang banyak. Sementara Marham, punya satu keinginan yang besar, bahwa ia ingin mati di kampung sendiri. Marham kini sudah dibawa jauh ribuan kilometer dari masa kecilnya, masa dimana ia mengenang suara-suara teriakan dari ibunya, memanggil ketika ia lupa waktu meloncat ke sungai, mencari ikan dan bertabuh gendang dalam air. Suara Marham yang paling nyaring, apalagi kalau mereka sudah bergelut dalam keruhnya sungai di dekat rumah. Ibunya paling kesal jika melihat Marham, lupa waktu. Ibunya tak ingin Marham melupakan shalat, sebab dalam shalat ada takwa yang sudah dijanjikan Tuhan.
“Marham, pulang!!!”
Kalau saja Marham sudah mendengar hal itu, ia lantas bergerak cepat. Menyusup di antara semak dan jalan setapak, ia lebih rela menyayat lengannya dengan tajamnya duri daripada harus bertemu dengan ibunya yang sudah menunggu di simpang jalan setapak bersama sebatang kayu bakar. Marham langsung meninggalkan sahabatnya. Ia berpacu dengan waktu untuk sampai ke rumahnya terlebih dahulu, membersihkan diri dan duduk untuk berpura-pura seakan-akan ibunya salah perkiraan. Ia duduk rapi di atas dipan reot yang dahulu dipahat bapaknya.
Marham tersenyum ketika ibunya datang. Apa yang bisa dilakukan seorang Ibu, ketika ia tak menemukan anaknya dalam keadaan bersih dan sedang menunggu datangnya Azan Maghrib. Ibunya hanya bisa tersenyum, meskipun ini sudah dilakukan Marham beratus kali, hampir setiap. Marham pun tersenyum dan mencium tangan ibunya.
“Marham kau memang pelita di hati Ibuk. Semenjak kepergian Bapakmu, kau lah yang menjadi penghibur hati dan kesepian di rumah ini”
Ya, kampung itulah, tepat dibelakang rumahnya ada kuburan Bapaknya. Disana ia ingin dikuburkan, dalam ketenangan desa dan sungai-sungai yang melaraskan alirannya lembut melewati bebatuan. Di kampung sunyi, sepi dan dipenuhi dengan teriakan bocah-bocah dari kejauhan tentang sungai-sungai, serta kebahagiaan.
Sebelum akhirnya ketika dewasa Marham beranjak dewasa dan mengenal kota. Ia liar seperti singa yang mengaum di tengah jalanan. Ia dibesarkan dari lorong ke lorong. Ia tinggalkan Ibunya, lantas mencari Ibukota. Ia menukar harapan kosong di kampung dengan gemerlapan wajah dunia. Setiap malam, ia duduk di gang-gang dengan sebilah belati tersarung di pinggangnya. Kalau sepi, ia beralih ke terminal bus antar kota, untuk menampar mimpi orang-orang kampung yang datang dengan harapan. Ia semakin ganas, ia merampas, menjambret dan membuat dirinya semakin kelam.
Dalam beberapa tahun ia menjadi tersohor, siapa yang tak kenal dengan Marham. Ia tak lagi membegal orang-orang, kini ia lebih terhormat. Ia duduk bersama orang-orang berdasi yang tenang menukar uang dengan sekumpulan bubuk terlarang. Marham menjadi mafia kelas kakap. Ia tak lagi turun dari angkutan umum, dari gang menuju gang, kini semua sudah berevolusi. Ia turun dari mobil mewah ke mobil mewah lainnya, ia tak kenal dengan sungai, yang ia sapa hanya suara gemerlapan malam dan suara dentuman musik yang membahana.
Marham tahu, jika saja ia dapat meloloskan transaksinya kali ini, ia akan berhasil menjadi manusia kaya. Dengan limpahan harta, ia besi membeli apa yang ia mau. Marham semakin menggebu, untuk memasukkan narkoba itu ke negara tetangga. Dalam pikirannya, ada hal yang menggerutu, ada bisikan datang dari Ibunya.
“Pelita hati... pelita hati...”
Marham mendengar bisikan gaib itu, menerka bahwa itu adalah panggilan rindu Ibunya. Namun rindu itu bias ke angkasa. Ia kembali meraih stirnya, mengemudikan laju kendaraannya di batas tol kota. Ia bersiap masuk dengan segala trik. Ia sudah menelan beberapa, memasukkan dalam bagasi serta menyusun rapi di pakaiannya. Ia pasti bisa melewati petugas bandara. Ia yakin sekali dengan kemampuannya itu.
Persis seperti penumpang lain, Marham bersiul dan masuk ke bandara. Seakan tak membawa apa-apa ia melenggang kangkung, dan benar saja ia lewat dari pintu pemeriksaan. Ia berhasil, dalam hatinya ada letusan gunung merapi yang membara bahagia. Segera ia melangkah cepat, menaiki eskalator. Pandangannya jatuh ke lantai mengeja langkah cepat, hingga pandangan itu terhenti pada barisan kaki-kaki kekar. Ia melongok pelan ke atas, dan hampir puluhan aparat bersenjata sudah mengepungnya. Marham kaku, terperangkap seperti singa diburu.
Di perahu, algojo itu semakin cepat mengayuh dayungnya. Marham, menghitung berapa lama lagi detik waktunya menemu maut. Matanya ditutup, tangannya diborgol besi, di balik malam yang dingin, kepalanya menciut pucat, gelap. Ada lima algojo yang mendayung, ia merasakan hangat tubuhnya. Tak ada perbincangan disana, lalu memori melintas tentang kampung, kesunyian dan gurau tawa. Bulan yang terang pun, hanya seberkas seperti kilatan cahaya yang menggumam dari kunang-kunang. Marham merasakan, mulai tak ada lagi suara orang-orang di kejauhan, mesin kapal atau apapun itu. Hanya gemericik air, yang didayung dan itu pun semakin pelan. Jantung Marham mendegup kencang, ia dipapah, diturunkan dari perahu.
“Sebentar-sebentar. Maaf, bolehkah penutup mataku dibuka?”
“Tidak bisa!”
“Bahkan untuk manusia yang terakhir kali melihat bulan pun kalian tidak perbolehkan?”, ucap Marham.
Algojo itu membuka penutup matanya, Marham dibawa ke dalam hutan. Disana ada lapangan luas yang terhampar. Marham melihat sekelilingnya dengan terang. Dinding-dinding bisu, lalu pagar berduri, ada anjungan mercusuar yang dijaga dengan senapan laras panjang. Ia terus berjalan dan bergerak menuju tengah lapangan. Disana sudah tegak tiang pancang. Tepat di depan tiang pancang itulah Marham akan mengasuh mautnya. Kembali dirapalkannya wajah kampung dan Ibuknya. Ia berjalan tergopoh ke tengah.
“Maaf, boleh aku berbisik sesuatu?”
Algojo itu pun kembali menuju ke arahnya.
“kuburkan aku di kampungku”
Mereka kembali melangkah menuju gerbang lapangan.
“dorr..., dorr..., dorr..., dorr..., dorr...”***
Rian Kurniawan Harahap
mahasiswa Pascasarjana UNRI. Menulis cerpen di beberapa harian lokal dan nasional.
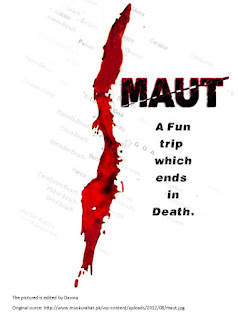

untuk informasi kesehatan bisa lihat Kamus Dokter
BalasHapus